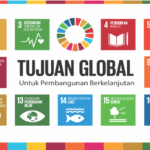Selama puluhan tahun, kita terutama di Indonesia, hidup dalam sebuah sistem yang membagi manusia menjadi dua kotak besar sejak usia 16 tahun: “Anak IPA” dan “Anak IPS”.
Anak IPA dianggap sebagai masa depan: para insinyur, dokter, dan ilmuwan. Mereka objektif, kuantitatif, dan memegang kunci “kemajuan”. Anak IPS, di sisi lain, mengurus hal-hal yang lebih “lunak”: hukum, ekonomi, dan sastra. Mereka subjektif, kualitatif, dan dianggap “kurang pasti”.
Kita mewarisi sebuah ‘perang’ budaya yang tidak kita mulai. Kita diberitahu bahwa ini adalah pembagian alami dunia—sains versus seni, logika versus rasa.
Kenyataannya, pemisahan ini adalah sebuah rekayasa sejarah yang belum terlalu lama. Dan kini, rekayasa itu mulai runtuh di hadapan kita.
Sejarah Singkat Sebuah Perceraian Intelektual
Selama ribuan tahun, pemisahan ini tidak ada. Bagi filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles, tidak ada bedanya antara mengamati anatomi oktopus (Biologi/STEM) dan merenungkan “kebaikan tertinggi” (Filsafat/Humaniora). Keduanya adalah bagian dari satu pencarian yang sama: kebijaksanaan (sophia).
Perceraian itu dimulai sekitar abad ke-17 saat Revolusi Ilmiah. Tokoh seperti Francis Bacon dan Isaac Newton mempopulerkan gagasan bahwa pengetahuan sejati haruslah sesuatu yang bisa diobservasi, diukur, dan diverifikasi. Jika tidak bisa diukur dengan angka, maka itu dianggap “tidak ilmiah”.
Di sinilah kita mulai memisahkan “kebenaran objektif” (milik Sains) dari “pengalaman subjektif” (milik Humaniora).
Pemisahan ini kemudian meledak menjadi perang budaya publik pada tahun 1959. Seorang fisikawan sekaligus novelis, C.P. Snow, mengeluh bahwa dunia intelektual telah terbelah menjadi “Dua Budaya”. Ia menuduh kaum sastrawan (Humaniora) sebagai “Luddites alami” (anti-teknologi) yang pesimis, sementara para ilmuwan (STEM) adalah kaum optimis yang “memiliki masa depan di tulang mereka”.
Di Indonesia, kita tidak hanya mengadopsi perdebatan ini; kita melembagakannya. Sistem penjurusan IPA/IPS adalah artefak dari ideologi pembangunan pasca-kemerdekaan. Narasi saat itu jelas: negara baru ini membutuhkan insinyur untuk membangun jembatan dan dokter untuk memberantas penyakit. Kemajuan diukur dengan PDB dan infrastruktur fisik. Anak IPA adalah mesin pembangunan. Anak IPS adalah kemewahan yang bisa menunggu.
Empat Mitos yang Kita Telan Bulat-Bulat
Hierarki nilai yang kita ciptakan ini—IPA di atas IPS—ditopang oleh beberapa mitos yang mendarah daging. Namun, jika kita melihat data dan sejarah lebih dekat, mitos-mitos itu mulai goyah.
Mitos 1: Anak STEM Pasti Kaya, Anak Humaniora Pasti Susah
Narasi ini mirip fabel “Kura-kura dan Kelinci”. Data jangka panjang menunjukkan bahwa lulusan STEM (Kelinci) hampir selalu memiliki gaji awal yang jauh lebih tinggi. Itu fakta. Keterampilan teknis mereka sangat dibutuhkan pasar.
Namun, saat memasuki usia puncak karier (usia 50-an), ceritanya berbalik. Lulusan Humaniora (Kura-kura) yang telah naik ke posisi manajerial dan kepemimpinan, pendapatannya secara signifikan menutup kesenjangan, bahkan sering kali melampaui rekan-rekan mereka.
Mengapa? Ternyata, keterampilan yang memberi Anda pekerjaan pertama (keterampilan teknis) berbeda dengan keterampilan yang memberi Anda promosi. Kemampuan komunikasi, pemahaman konteks manusia, penalaran etis, dan empati—keterampilan inti Humaniora—menjadi sangat mahal harganya di tingkat kepemimpinan.
Mitos 2: Silicon Valley Dibangun Murni oleh ‘Anak Teknik’
Kita mengira pusat teknologi dunia adalah kuil suci bagi para engineer dan coder. Kita membayangkan para pendirinya adalah ‘Anak IPA’ super jenius yang hidup dari algoritma. Kenyataannya, banyak dari arsitek paling sukses di era digital justru tidak memiliki latar belakang STEM murni.
Mereka berhasil bukan meskipun memiliki gelar Humaniora, tetapi karena gelar tersebut.
- Stewart Butterfield, co-founder dari Slack (alat kolaborasi tim yang dipakai jutaan orang), memiliki gelar S1 dan S2 di bidang Filsafat. Dia tidak sedang membangun kode murni; dia menerapkan pemahaman filosofis tentang interaksi manusia dan dinamika sosial yang kompleks untuk membangun alat yang intinya adalah tentang kolaborasi.
- Reid Hoffman, co-founder dari LinkedIn, memiliki gelar Master di bidang Filsafat dari Oxford. Dia secara eksplisit menyatakan bahwa dia mengambil “pendekatan filosofis terhadap bisnis,” berfokus pada pemecahan “masalah manusia” (seperti karier dan jaringan profesional) dan bagaimana teknologi bisa menjadi mediumnya.
- Susan Wojcicki, mantan CEO YouTube, mengambil jurusan Sejarah dan Sastra. Latar belakang ini memberinya keahlian yang sempurna untuk mengelola platform yang pada intinya bukanlah tentang coding kompresi video, melainkan tentang cerita manusia, ekspresi budaya global, dan komunikasi massa.
Ini adalah pola yang jelas. Latar belakang STEM memberi tahu Anda cara membangun produk. Latar belakang Humaniora memberi tahu Anda mengapa manusia mungkin menginginkan atau membutuhkan produk tersebut. Para pemimpin ini memahami bahwa teknologi bukanlah tentang kode; ini tentang interaksi manusia yang dimediasi oleh kode.
Mitos 3: “STEM” Adalah Kategori Ilmu yang Fundamental
Kita berbicara tentang “STEM” seolah-olah itu adalah kategori pengetahuan kuno yang sakral. Kenyataannya, akronim ini sangat baru dan asal-usulnya konyol.
Pada 1990-an, National Science Foundation (NSF) Amerika Serikat menggunakan akronim “SMET” (Science, Mathematics, Engineering, Technology) untuk lobi pendanaan. Tapi akronim ini tidak laku. “SMET” terdengar tidak enak, bahkan mirip dengan kata “smut” (cabul). Akhirnya, sekitar tahun 2001, mereka membaliknya menjadi “STEM” hanya karena terdengar lebih baik.
“STEM” bukanlah entitas filosofis yang koheren. Itu adalah merek kebijakan (policy brand) abad ke-21 yang dibuat untuk kenyamanan lobi anggaran. Perang “STEM vs Humaniora” sebenarnya adalah perang antara dua label buatan.
Mitos 4: Sains Bekerja di Ruang Hampa, Terpisah dari Makna
Ini mungkin mitos terbesar. Kita membayangkan ilmuwan murni di laboratorium, hanya berurusan dengan data objektif, terpisah dari kekacauan moral dan emosi manusia. Mari kita uji mitos ini dengan studi kasus paling ekstrem: J. Robert Oppenheimer.
Oppenheimer adalah lambang supremasi STEM abad ke-20. Dia adalah fisikawan teoretis yang memimpin Proyek Manhattan—proyek raksasa yang mengerahkan ribuan ilmuwan untuk menciptakan bom atom. Otaknya jelas penuh dengan persamaan fisika dan data teknis.
Namun, Oppenheimer juga seorang humanis yang gelisah. Dia secara khusus mendedikasikan waktunya untuk belajar bahasa Sanskerta (disiplin Humaniora klasik) agar bisa membaca teks Hindu kuno, Bhagavad Gita, dalam bahasa aslinya.
Saat momen puncak karier STEM-nya tiba—ledakan uji coba nuklir pertama pada 16 Juli 1945—kedua dunia ini bertabrakan di dalam benaknya. Kalimat yang muncul di pikirannya untuk memahami apa yang baru saja ia saksikan bukanlah formula fisika.
Kalimat itu datang dari Bhagavad Gita, yang ia terjemahkan sendiri: “Sekarang saya menjadi Maut, sang penghancur dunia.”
Ini adalah bukti nyata yang paling kuat: STEM memberi tahu kita cara membelah atom. Humaniora menyediakan kerangka kerja untuk memahami makna dan konsekuensi etis dari tindakan tersebut. Oppenheimer membutuhkan lensa humanistiknya untuk memproses krisis moral yang baru saja diciptakan oleh kejeniusan STEM-nya. Sains memberi kita kekuatan; Humaniora memaksa kita bergulat dengan pertanyaan apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan itu.
Dan Kemudian, AI Datang Mengubah Segalanya
Jika perdebatan ini sudah goyah selama puluhan tahun, AI Generatif adalah meteor yang datang untuk mengakhirinya secara tuntas.
Selama ini, argumen utama orang tua di Indonesia adalah: “Belajar STEM (IPA) agar aman dari otomatisasi.” AI Generatif baru saja membalikkan meja tersebut.
AI kini terbukti sangat mahir dalam tugas-tugas teknis rutin—seperti coding (pemrograman) tingkat dasar-menengah, menganalisis data, dan bahkan menulis laporan teknis. Ini, pada dasarnya, adalah banyak dari “pekerjaan anak IPA” yang kita agung-agungkan.
Lalu, apa yang tidak bisa dilakukan AI? Penilaian (judgement).
Nilai ekonomi manusia kini bergeser drastis: dari eksekusi teknis (yang bisa dilakukan AI) ke penghakiman humanis (yang tidak bisa dilakukan AI). Keterampilan yang tiba-tiba menjadi paling berharga di pasar adalah:
- Kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat (prompt engineering), yang pada dasarnya adalah seni retorika dan logika.
- Kurasi kritis, yaitu kemampuan membedakan mana output AI yang berkualitas, mana yang “sampah”, dan mana yang bias secara etis.
- Pemahaman etika, untuk memutuskan kapan dan di mana teknologi ini tidak boleh digunakan.
- Kecerdasan emosional, kemampuan untuk berkolaborasi, berempati, dan memimpin tim manusia yang kini bekerja bersama AI.
Intinya, AI Generatif secara ironis mengotomatisasi banyak keterampilan teknis STEM tingkat menengah, dan secara drastis menaikkan nilai serta harga dari keterampilan inti Humaniora.
Re-Integrasi Paksa: Lahirnya STEAM dan Manusia Hibrida
Hasil dari guncangan AI ini adalah re-integrasi paksa dari kedua budaya. Tren terbesar dalam pendidikan dan industri saat ini adalah penambahan huruf ‘A’ (untuk Arts atau Humaniora) ke dalam akronim, mengubah STEM menjadi STEAM.
Ini bukan sekadar upaya kosmetik untuk membuat sains ‘lebih menyenangkan’ dengan pelajaran menggambar. Ini adalah koreksi pasar (market correction) yang brutal, yang didorong oleh industri teknologi itu sendiri.
Selama bertahun-tahun, fokus STEM murni telah terbukti menghasilkan produk yang brilian secara teknis, namun seringkali cacat secara manusiawi. Produk-produk itu sulit digunakan, tidak intuitif, atau sama sekali tidak memahami psikologi penggunanya.
Industri akhirnya sadar:
- STEM menyediakan fungsionalitas teknis.
- ‘A’ (Humaniora) menyediakan kreativitas, desain yang berpusat pada manusia (human-centered design), pemahaman estetika, dan pemahaman psikologis pengguna.
Sebuah produk bisa berfungsi secara teknis (STEM), tetapi jika desainnya buruk atau tidak memahami kebutuhan psikologis penggunanya (‘A’), produk itu akan gagal di pasar.
Pendidikan STEM murni telah menciptakan apa yang disebut sebagai “defisit empati”. STEAM adalah imperatif ekonomi untuk memperbaikinya. Perusahaan teknologi tidak lagi hanya mencari coder, mereka mencari problem-solver yang hibrida.
Sederhananya: STEM membangun robot; STEAM mempertanyakan apa implikasi etis dan bagaimana antarmuka manusia dari robot tersebut.
Hasilnya adalah ledakan bidang-bidang “hibrida” baru di universitas dan industri. Ini bukan lagi teori; ini adalah lowongan pekerjaan yang nyata.
Lihat saja bidang Etika AI dan Tata Kelola Teknologi. Ini adalah arena hibrida yang paling cepat meledak. Perusahaan teknologi raksasa seperti IBM dan Microsoft kini secara aktif mempekerjakan Filsuf, Sosiolog, dan Ahli Hukum (Humaniora) untuk bekerja berdampingan dengan para insinyur (STEM). Tujuannya bukan untuk berbaik hati, tapi murni manajemen risiko: mereka butuh kaum humanis untuk memastikan produk AI mereka tidak diskriminatif, bias, atau berbahaya secara sosial.
Atau lihat Humaniora Digital (Digital Humanities). Di bidang ini, para sejarawan, sastrawan, dan arkeolog tidak lagi hanya membaca buku satu per satu. Mereka menggunakan alat-alat STEM—seperti analisis big data, pemodelan 3D, dan pemetaan GIS—untuk menjawab pertanyaan Humaniora. Bayangkan seorang sejarawan yang bisa melacak evolusi sebuah ide dengan menganalisis ribuan teks kuno secara serentak, atau seorang arkeolog merekonstruksi situs sejarah yang telah hancur secara digital.
Ada juga Ilmu Sosial Komputasi (Computational Social Science). Bidang ini menggunakan kekuatan komputasi masif (STEM) untuk memodelkan dan menganalisis perilaku manusia dan fenomena sosial (Humaniora) dalam skala yang sebelumnya mustahil, seperti memprediksi penyebaran informasi atau memahami dinamika kerumunan dalam skala besar.
Tantangan Sebenarnya: Mengapa ‘STEAM’ Bukan Solusi Ajaib
Namun, apakah menambahkan huruf ‘A’ ke dalam akronim lantas menyelesaikan masalah selama ratusan tahun? Tentu saja tidak. Di lapangan, implementasi STEAM dan bidang hibrida ini menghadapi tantangan besar.
Integrasi sejati berarti menggunakan metodologi Humaniora (seperti pemikiran kritis dan etika) untuk menantang proyek STEM itu sendiri. Tapi ini sulit, dan membawa kita pada hambatan terbesar: keterbatasan pendidik. Model STEAM secara implisit menuntut guru untuk menjadi polymath (ahli di banyak bidang). Namun, sistem pendidikan kita—dari S1 hingga program pelatihan guru—dirancang untuk menghasilkan spesialis.
Seorang guru fisika, produk pelatihan IPA murni, mungkin sangat ahli di bidangnya tetapi merasa sangat tidak nyaman dan tidak kompeten memimpin diskusi etis yang bernuansa. Sebaliknya, seorang guru seni mungkin tidak memahami batasan rekayasa (engineering constraints) yang dihadapi siswa. Seperti yang ditunjukkan data dari Indonesia, guru di lapangan melaporkan kebutuhan kritis akan “dukungan pedagogik” dan “pelatihan teknis”. Kita tidak bisa mengharapkan pendidik yang dilatih di pabrik spesialisasi abad ke-20 (IPA/IPS) untuk tiba-tiba membangun siswa hibrida abad ke-21.
Masalah paling mendasar adalah penilaian (asesmen). Bagaimana Anda menilai proyek hibrida? Komponen STEM memiliki jawaban ‘benar’ atau ‘salah’ yang objektif (“Apakah jembatannya rubuh?”). Komponen Humaniora bersifat interpretatif dan subjektif (“Apakah desainnya ‘etis’?”). Ini adalah ‘Perang Dua Budaya’ C.P. Snow yang terjadi di dalam satu lembar rapor siswa.
Terakhir, ada risiko ‘kedangkalan’ (depth vs. breadth). Dengan menambahkan ‘A’ ke dalam kurikulum yang sudah padat, ada risiko nyata bahwa siswa tidak mempelajari apa pun secara mendalam. Kritik umum adalah bahwa STEAM mengorbankan ketelitian teknis (technical rigor) demi proyek yang “menyenangkan”, menciptakan generasi “Jack of all trades, master of none”.
Ada kontradiksi kritis di sini: gerakan STEAM mendorong keluasan (breadth), sementara penelitian pendidikan mapan menunjukkan bahwa kedalaman (depth) adalah prediktor kesuksesan jangka panjang. Sebuah studi besar menemukan bahwa siswa yang belajar lebih sedikit topik sains tetapi mendalam (misalnya, satu bulan penuh pada satu topik) mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi di perguruan tinggi daripada mereka yang “kebut” semua topik di buku teks secara dangkal.
Tanpa revolusi dalam pelatihan guru dan cara kita menilai, implementasi STEAM yang naif bisa menjadi bumerang—memperburuk masalah kedangkalan sambil mengorbankan ketelitian.
Penutup: Selamat Datang, Manusia Hibrida
Dikotomi “STEM vs Humaniora” adalah konstruksi sejarah yang sudah kedaluwarsa. Perang budaya itu sudah selesai, dan AI adalah lonceng kematiannya.
Lalu, apa yang harus kita lakukan, khususnya dalam konteks Indonesia? Analisis ini menyisakan beberapa rekomendasi kebijakan yang mendesak:
- Sudahi Perdebatan Akronim (STEM vs. STEAM). Fokus pembuat kebijakan seharusnya bukan lagi memperdebatkan huruf mana yang akan ditambah atau dihapus. Fokusnya harus beralih dari integrasi dangkal ke pengembangan literasi ganda (dual literacy) yang mendalam bagi semua siswa.
- Bongkar Penjurusan Dini (IPA/IPS). Model penjurusan kaku di sekolah menengah adalah warisan dari era pembangunan abad ke-20 yang sudah usang. Itu harus diganti dengan kurikulum inti yang lebih fleksibel, yang mewajibkan semua siswa mencapai kompetensi inti baik dalam literasi komputasional/data (inti dari IPA) maupun dalam literasi kritis/etis (inti dari IPS/Humaniora).
- Berinvestasi Besar-besaran pada Pendidik Hibrida. Hambatan terbesar untuk reformasi adalah guru. Kita tidak bisa mengharapkan pendidik yang dilatih di “pabrik” spesialisasi abad ke-20 untuk menciptakan siswa hibrida abad ke-21. Indonesia harus merombak universitas keguruan (LPTK) dan berinvestasi besar-besaran dalam pelatihan untuk melahirkan guru yang “fasih” dalam kedua metodologi (kuantitatif dan kualitatif).
- Akui Bahwa “Soft Skills” adalah “Hard Skills” Ekonomi. Pemerintah harus memperluas definisi “Talenta Digital”. Harus ada pengakuan formal bahwa keterampilan seperti komunikasi, empati, dan pemikiran kritis bukanlah “soft skills”. Di era AI, itu adalah keterampilan ekonomi yang paling sulit, paling berharga, dan paling “keras” (hard skills). Keterampilan ini harus didanai dan dilatih dengan ketat, sama seriusnya dengan pelatihan teknis.
Masa depan tidak akan dimiliki oleh pembuat kode (STEM) atau oleh kritikus (Humaniora) saja. Masa depan akan dimiliki oleh mereka yang “bilingual” secara intelektual.
Mereka adalah para insinyur yang bisa merenungkan etika dari apa yang mereka bangun, dan para sastrawan yang bisa memahami bagaimana algoritma membentuk opini publik.
Tugas kita di abad ke-21 bukanlah memaksa anak muda memilih satu “budaya” dan mengunci diri di sana. Tugas kita adalah memberi mereka peta dan paspor untuk bisa bernavigasi dengan nyaman di kedua wilayah tersebut. Karena masalah paling pelik di dunia dari perubahan iklim hingga disrupsi AI bersifat sosio-teknis. Masalah-masalah itu tidak bisa dipecahkan hanya dengan rumus atau hanya dengan rasa. Kita butuh keduanya.