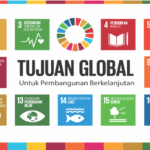Kalau kita perhatikan berita beberapa tahun terakhir, rasanya dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang tarif antara kekuatan besar, rantai pasok global yang kacau, dan konflik yang meletus di berbagai penjuru. Kita mungkin berpikir, inilah ancaman terbesar bagi perekonomian dan bisnis di Indonesia.
Logikanya sederhana: jika dunia sedang ‘sakit’, kita pasti ikut tertular.
Tapi apa yang saya temukan baru-baru ini mengubah cara pandang saya. Ternyata, para pemimpin bisnis di Indonesia—orang-orang yang setiap hari mengurus pabrik, ekspor, dan mempekerjakan ribuan orang—memiliki kekhawatiran yang sangat berbeda.
Saat para CEO di London, New York, dan Shanghai pusing memikirkan “volatilitas makroekonomi” global, para bos di Indonesia justru pusing memikirkan “ketidakpastian regulasi” dan “biaya logistik” di dalam negeri.
Ini adalah sebuah pemisahan (decoupling) sentimen yang sangat fundamental. Dunia melihat ke luar dengan cemas. Kita, ternyata, sedang sibuk bertarung di dalam.
Paradoks Sentimen: ‘Decoupling’ Indonesia dari Global
Di sinilah letak keunikan dan tesis utama artikel ini. Mari kita bedah pemandangannya.
Secara global, para pemimpin bisnis sedang pusing. Ketika ditanya apa ancaman terbesar mereka untuk tahun 2025, jawabannya sangat spesifik. Bagi 29% CEO global, ancaman teratas adalah “volatilitas makroekonomi”. Bagi 27% lainnya, itu adalah “inflasi”. Ini adalah bahasa formal untuk “kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan.”
Ancaman besar kedua? “Resesi Geopolitik”. Ini adalah sebuah istilah baru yang menggambarkan era di mana tatanan global sedang terpecah-belah. Negara-negara kembali membangun ‘pagar’, menerapkan proteksionisme, dan mengobarkan perang tarif. Aturan main global sedang ditulis ulang, dan itu membuat masa depan terasa sangat tidak pasti.
Anehnya, di tengah semua ketakutan ini, mayoritas CEO global (58%) justru optimis ekonomi global akan membaik.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di sinilah terjadi ‘decoupling’ atau pemisahan. Para CEO di sini (menurut survei PwC) melihat kekacauan global yang sama dan mengambil kesimpulan yang berlawanan. Mereka justru lebih pesimis mengenai prospek ekonomi global dibandingkan siapa pun di dunia. Mereka melihat ketidakpastian itu dan berpikir: “Ya, dunia sedang benar-benar berantakan.”
Tapi—dan inilah inti paradoksnya—di saat yang sama, mereka secara bersamaan justru jauh lebih optimis tentang prospek ekonomi domestik.
APINDO, misalnya, memproyeksikan potensi investasi di Indonesia pada tahun 2025 akan “cenderung lebih tinggi”. Mengapa? Karena optimisme mereka tidak lagi berlabuh pada apa yang terjadi di Washington atau Beijing. Optimisme mereka bersumber murni dari persepsi “stabilitas internal”. Proyeksi pertumbuhan PDB kita masih solid, ditargetkan di angka 5,1% hingga 5,4% untuk 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kokoh.
Mereka seolah berkata, “Dunia boleh saja kacau. Selama di dalam negeri aman dan proyeksi kita masih 5%, kami akan baik-baik saja.”
Identifikasi Ancaman Riil: ‘Isu Klasik’ Domestik
Ini langsung memunculkan pertanyaan: mengapa? Jika optimisme para pengusaha kita ada di dalam negeri, berarti ancaman terbesar mereka juga pasti ada di dalam negeri.
Inilah penjelasan inti dari tesis artikel ini.
Ketika ditanya apa hambatan investasi terbesar untuk tahun 2025, para pengusaha (APINDO) tidak menunjuk pada perang dagang AS-Tiongkok atau konflik di Timur Tengah. Mereka menunjuk pada “isu klasik” domestik.
Para pengusaha menyebutnya “isu klasik”. Saya lebih suka menyebutnya “Tarif Internal”. Ini adalah biaya tak terlihat yang harus kita bayar, bukan karena persaingan global, tapi karena kerumitan yang kita ciptakan sendiri.
‘Tarif Internal’ ini memiliki dua wajah utama:
Pertama, ketidakpastian regulasi. Ini adalah ancaman nomor satu. Bagi seorang pengusaha, tidak ada yang lebih menakutkan daripada aturan main yang terus berubah. Ini bukan hanya soal “susah izin”, tapi soal “gap implementasi”—apa yang tertulis indah dalam kebijakan di Jakarta seringkali sangat berbeda dengan realitas di lapangan yang dihadapi di pelabuhan atau pabrik di daerah.
Kedua, biaya struktural yang sangat tinggi. Ini adalah beban konkret yang bisa dihitung. Biaya logistik kita, misalnya, masih ‘nyangkut’ di angka 14,29% dari PDB. Untuk memberi Anda gambaran, angka ini begitu kronis sampai-sampai target jangka panjang pemerintah adalah menurunkannya menjadi 8% pada tahun 2045. Ini adalah pertarungan puluhan tahun.
Bayangkan Anda seorang pengusaha garmen di Jawa Tengah. Sebelum Anda pusing memikirkan tarif bea masuk di Eropa, Anda sudah harus pusing lebih dulu memikirkan biaya truk yang 14,29% itu.
Tidak berhenti di situ, Anda harus menghadapi ‘tarif internal’ lain yang tak terlihat: Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Measures/NTM). Ini adalah istilah halus untuk birokrasi yang berbelit, aturan sertifikasi SNI yang rumit, persetujuan impor yang lama, dan pembatasan pelabuhan masuk.
Inilah mengapa fokus mereka 100% ada di dalam. Untuk apa khawatir soal perang dagang yang abstrak di TV, jika musuh yang nyata—berupa biaya truk dan tumpukan formulir—ada di depan mata setiap hari?
Biaya Peluang yang Hilang: Kegagalan Menangkap Momentum ‘China Plus One’
Fokus pada ‘musuh internal’ ini bukan sekadar keluhan manja. Ini adalah respons logis, karena kerumitan ini sudah memakan biaya. Kita sudah kehilangan sebuah peluang emas.
Selama puluhan tahun, dunia menjadikan Tiongkok sebagai ‘pabrik dunia’. Tapi, beberapa tahun terakhir, ketegangan geopolitik dan perang dagang membuat strategi itu goyah. Perusahaan multinasional raksasa sadar mereka tidak bisa menaruh semua telur di satu keranjang.
Muncullah strategi “China Plus One”.
Mereka mulai mencari ‘rumah baru’ untuk pabrik mereka, mencari lokasi alternatif untuk mendiversifikasi rantai pasok mereka. Ini adalah pergeseran investasi manufaktur terbesar dalam satu generasi.
Siapa yang seharusnya menjadi ‘rumah baru’ paling ideal di Asia Tenggara? Tentu saja Indonesia. Kita punya segalanya: populasi terbesar, pasar domestik yang kuat, dan sumber daya alam yang melimpah.
Tapi apa yang terjadi? Ke mana perginya investasi triliunan rupiah itu?
Data menunjukkan, mereka mengalir deras ke negara tetangga kita. Vietnam dan Malaysia menjadi penerima manfaat utama, merebut investasi-investasi manufaktur baru tersebut.
Mengapa mereka melewatkan kita?
APINDO memberikan jawaban yang jujur dan menyakitkan: Indonesia “tidak bisa menangkap peluang tersebut”. Alasannya? “Kurangnya dukungan iklim usaha sektoral.”
‘Iklim usaha sektoral’ itu adalah bahasa lain dari ‘isu klasik’ dan ‘tarif internal’ yang kita bahas tadi. Para investor global itu melihat kerumitan kita—birokrasi NTM yang berbelit, biaya logistik 14,29%, dan regulasi yang tidak pasti—dan mereka memutuskan: “Tidak, terima kasih. Terlalu berisiko.”
Kita tidak kalah karena kurang sumber daya. Kita kalah karena kita rumit. Vietnam dan Malaysia tidak menawarkan sumber daya lebih baik; mereka ‘hanya’ menawarkan kepastian dan efisiensi. Ternyata, di era ini, itulah segalanya.
Pertarungan ‘Software’: Punya Produk, Tapi Tersendat di Strategi
Tapi cerita ini belum selesai. Ternyata, ‘isu klasik’ itu punya lapisan kedua. Masalah kita bukan hanya ‘perangkat keras’ (hardware) berupa regulasi dan pelabuhan. Kita juga punya tantangan besar di sisi ‘perangkat lunak’ (software): kapasitas sumber daya manusia dan strategi bisnis.
Ini adalah “isu klasik” lainnya yang sering luput. Data menunjukkan gambaran yang mencengangkan. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 66 juta pelaku UMKM. Mereka adalah tulang punggung ekonomi kita.
Tapi coba tebak berapa banyak dari mereka yang aktif mengekspor? Hanya sekitar 35.000 hingga 40.000.
Itu adalah kesenjangan kapasitas yang luar biasa besar. Padahal, target nasional adalah menciptakan 500.000 eksportir baru pada tahun 2030.
Para pemimpin bisnis mengidentifikasi ini sebagai “pain point klasik”: para pelaku UMKM kita “memiliki produk berkualitas, namun tersendat di strategi”.
Ini memperjelas masalahnya. Anggaplah besok semua regulasi beres dan biaya logistik jadi 8%. Apakah ‘hadiah’ 35% peningkatan ekspor itu otomatis cair? Ternyata tidak.
Mengapa? Karena kita juga harus membenahi para pemainnya. Para eksportir kita perlu mengubah pola pikir, dari yang “reaktif” (menunggu kesempatan datang) menjadi “asertif” (menyiapkan strategi dan menjemput bola).
Ini menegaskan lagi: pertarungan terbesar kita ada di dalam. Pertarungan melawan birokrasi dan pertarungan melawan mediokritas strategi kita sendiri.
Jalan ke Depan: Kuantifikasi ‘Hadiah’ dari Reformasi Internal
Di sinilah kita menemukan resolusi strategisnya. Fokus ke dalam negeri bukan hanya soal bertahan hidup. Ini adalah soal membuka potensi terbesar kita.
Ini adalah jawaban untuk pertanyaan “lalu kenapa?”. Lalu kenapa kita harus repot-menerapkan ‘tarif internal’ dan kesenjangan kapasitas ini?
Karena ‘hadiah’ yang menunggu di garis finis sangat besar dan jauh lebih pasti daripada keuntungan apa pun yang bisa kita dapatkan dari mencoba menavigasi kekacauan geopolitik global.
Para pelaku bisnis kita tidak tinggal diam. Secara eksternal, mereka cerdas bermanuver. KADIN secara proaktif memimpin misi dagang ke India, mencari koridor perdagangan baru yang lebih aman.
Tapi pertarungan sesungguhnya, dan hadiah terbesarnya, ada di internal. Kita harus membenahi ‘perangkat keras’ (regulasi dan logistik) dan ‘perangkat lunak’ (SDM dan strategi).
Bank Dunia telah membantu kita mengkuantifikasi ‘hadiah’ dari pembenahan ‘perangkat keras’ saja.
Dalam analisis mereka, jika Indonesia berhasil mereformasi empat kategori utama NTM—hal-hal sederhana seperti menyederhanakan persetujuan impor, sertifikasi SNI, dan pembatasan pelabuhan—hasilnya bukanlah kenaikan biasa.
Potensi peningkatannya luar biasa:
- Peningkatan PDB: Sekitar 10% di atas baseline.
- Peningkatan Ekspor: Sekitar 35% di atas proyeksi normal.
- Peningkatan Investasi: Sekitar 30% di atas proyeksi normal.
Mari kita resapi angka-angka ini. 10%, 35%, dan 30%. Angka ini adalah segalanya. Ini adalah bukti matematis bahwa pemicu pertumbuhan terbesar Indonesia tidak terletak di Washington atau Beijing. Pemicunya ada di kantor-kantor pemerintahan kita di Jakarta.
Inilah alasan mengapa fokus internal sangat penting. Untuk apa kita menghabiskan energi mencoba memprediksi langkah Donald Trump atau Xi Jinping, jika ada potensi peningkatan ekspor sebesar 35% yang bisa kita ‘buka’ hanya dengan membereskan birokrasi kita sendiri?
Pertarungan Terbesar Kita
Ini membawa saya pada sebuah kesimpulan personal yang radikal.
Selama ini, kita mungkin terlalu sering diajarkan untuk menyalahkan ‘kekuatan luar’ atas masalah kita. Entah itu globalisasi yang tidak adil, pasar yang bergejolak, atau kepentingan asing.
Tapi data ini menunjukkan cerita yang berbeda. Cerita yang jauh lebih dekat dengan rumah.
Ternyata, pertarungan terbesar Indonesia di era fragmentasi global ini bukanlah melawan dunia. Pertarungan terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri—melawan inefisiensi, birokrasi yang berbelit, dan keengganan kita untuk berubah.
Ini adalah kabar baik.
Jika musuh ada di luar, kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi karena musuh terbesarnya ada di dalam, maka solusinya 100% ada di genggaman kita.
Di tengah kekacauan global, pemenangnya bukanlah negara yang paling kuat secara militer atau yang paling kaya sumber dayanya. Pemenangnya adalah negara yang paling efisien, paling cepat beradaptasi, dan paling gigih membereskan ‘rumah’-nya sendiri.