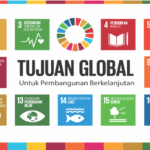Saya sering mengajak pembaca untuk merenungkan kembali bagaimana dunia ini bekerja. Jika kita melihat sejarah panjang peradaban manusia, ilmu pengetahuan selalu dianggap sebagai api suci yang menerangi kegelapan. Dari Galileo hingga Einstein, narasi yang kita percayai adalah bahwa sains bergerak demi kemajuan umat manusia semata.
Namun, jika kita menyingkap lapisan romantis tersebut dan melihat struktur ekonominya hari ini, kita akan menemukan sebuah paradoks yang mengejutkan.
Mari kita bayangkan sebuah model bisnis impian. Dalam bisnis ini, bahan baku Anda didapatkan secara gratis. Orang-orang yang memeriksa kualitas produk Anda (quality control) juga bekerja tanpa bayaran. Pasar Anda adalah institusi yang ‘wajib’ membeli produk tersebut tanpa mempedulikan harga. Dan yang paling hebat, Anda menjual kembali produk tersebut kepada orang-orang yang sama yang memberikan bahan bakunya kepada Anda secara cuma-cuma.
Terdengar mustahil? Terdengar seperti skema yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan?
Inilah realitas bisnis jurnal akademik global saat ini. Sebuah industri yang beroperasi dalam bayang-bayang menara gading, namun memegang kendali penuh atas siapa yang berhak didengar dan siapa yang dibungkam dalam panggung sains dunia.
Anomali Keuntungan: Dominasi Oligopoli dan Profitabilitas “Tidak Wajar”
Kita hidup di era di mana Google dan Apple dianggap sebagai puncak kesuksesan kapitalisme. Kita sering kali kagum pada kekayaan mereka. Namun, jika kita membedah laporan keuangannya, ada fakta yang jarang dibicarakan: persentase keuntungan operasional penerbit jurnal ilmiah raksasa sering kali mengalahkan perusahaan teknologi terbesar di dunia tersebut.
Pasar penerbitan ilmiah tidak beroperasi dengan hukum ekonomi normal, melainkan dikuasai oleh struktur oligopoli yang ketat. Hanya segelintir pemain, yang kita kenal sebagai “The Big 5” (Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, dan SAGE), secara efektif mengontrol lebih dari 50% arus pengetahuan ilmiah di seluruh dunia. Apa pun disiplin ilmunya, kemungkinan besar riset tersebut diterbitkan oleh salah satu dari kelima raksasa ini.
Bagaimana mereka bisa begitu berkuasa? Temuan kuncinya ada pada margin keuntungan operasional mereka yang secara konsisten menyentuh angka 30% hingga 40%. Angka ini melampaui margin rata-rata Google atau Apple yang biasanya berkisar di 25-30%. Padahal, Google harus membayar ribuan insinyur mahal, membeli server data center, dan membangun pabrik perangkat keras.
Rahasia di balik profitabilitas “tidak wajar” ini terletak pada rantai pasoknya yang unik. Dalam industri manufaktur biasa, produsen harus membeli bahan baku. Namun dalam industri ini, penerbit mendapatkan bahan baku (naskah riset) secara gratis dari para dosen dan peneliti.
Lebih jauh lagi, mereka juga mendapatkan layanan kontrol kualitas (peer review) secara cuma-cuma dari komunitas akademik yang sama atas nama “pengabdian profesional”. Penerbit kemudian mengemas produk gratisan ini, memberi label merek jurnal, dan menjualnya kembali dengan harga premium kepada universitas—tempat di mana para penulis dan reviewer itu bekerja.
Ini adalah bentuk kapitalisme jenius sekaligus tragis. Kita sedang melihat transfer kekayaan publik yang masif menuju segelintir korporasi swasta di Eropa dan Amerika Utara, sebuah model bisnis yang memanfaatkan idealisme ilmuwan demi keuntungan pemegang saham.
Transisi Model Bisnis: Jebakan “Open Access” dan Neokolonialisme Baru
Tidak berhenti pada margin keuntungan, industri ini kini sedang mengalami pergeseran tektonik dalam cara mereka menarik uang. Kita sedang menyaksikan transisi masif dari model bisnis tradisional “bayar untuk membaca” (berlangganan) menjadi model “bayar untuk terbit” (Open Access).
Sekilas, perubahan ini terdengar sangat demokratis dan pro-rakyat. Narasi yang dibangun adalah: “Ilmu pengetahuan harus gratis untuk semua orang!” Siapa yang tidak setuju? Dengan model Open Access, siapa pun—dari mahasiswa di pelosok Kalimantan hingga petani di pedesaan—bisa mengakses jurnal ilmiah terbaru tanpa terhalang tembok berbayar (paywall).
Namun, ada satu detail kecil yang sering luput dari perhatian publik: Penerbit tidak pernah menghilangkan tembok penghalang tersebut; mereka hanya memindahkannya.
Jika dulu tembok itu berdiri di depan pembaca, kini tembok itu digeser ke depan penulis. Untuk bisa menerbitkan artikel di jurnal Open Access bergengsi, penulis (atau institusinya) diwajibkan membayar biaya yang disebut Article Processing Charges (APC).
Inisiatif seperti Plan S di Eropa, yang dengan agresif mewajibkan semua riset didanai publik harus terbuka, secara tidak sengaja memperburuk keadaan ini bagi negara berkembang. Bagi peneliti di Oxford atau Berlin yang didukung dana hibah euro yang melimpah, biaya ini hanyalah angka di kertas anggaran. Namun bagi peneliti dari Global South (Negara Selatan), ini adalah bencana eksklusi.
Kita sedang melihat lahirnya bentuk “neokolonialisme epistemik” baru. Sistem ini secara efektif menyaring siapa yang boleh bersuara di panggung dunia. Hanya mereka yang punya modal besar yang bisa memproduksi “kebenaran ilmiah” yang diakui secara global. Sementara peneliti dari negara berkembang, yang mungkin memiliki temuan brilian namun miskin dana, perlahan-lahan tersingkir atau terpaksa menerbitkan karya di jurnal kelas dua yang kurang dibaca.
Biaya untuk menembus tembok baru ini pun tidak main-main. Di jurnal-jurnal top dunia, biaya APC per satu artikel bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Fakta Jarang Diketahui: Ironi Ekonomi di Balik Menara Gading Indonesia
Jika kita mempersempit lensa (zoom in) ke tanah air, dampak dari pergeseran model bisnis ini terasa jauh lebih personal dan menyakitkan. Ada beberapa fakta yang jarang diungkap ke publik, yang menunjukkan betapa timpangnya realitas ekonomi dosen di Indonesia dibandingkan dengan tuntutan global yang mereka hadapi.
1. Gaji Dosen vs. Biaya Terbit: Matematika yang Tidak Masuk Akal Mari kita bicara data riil. Gaji pokok seorang dosen pemula (Asisten Ahli/Lektor) di banyak perguruan tinggi swasta maupun negeri di Indonesia sering kali masih berkisar di angka Rp 2.500.000 hingga Rp 4.000.000 per bulan (di luar tunjangan yang pencairannya kadang tidak menentu).
Sekarang, bandingkan dengan “harga tiket” untuk masuk ke panggung jurnal internasional bereputasi (Q1/Q2). Biaya Article Processing Charge (APC) rata-rata berkisar antara $2.000 hingga $3.500. Jika dikonversi ke Rupiah, ini setara dengan Rp 30 Juta hingga Rp 52 Juta per satu artikel.
Untuk jurnal level dewa seperti Nature, biayanya bahkan bisa menembus Rp 150 Juta per artikel.
Fakta ini melahirkan sebuah ironi yang tragis: Seorang dosen di Indonesia mungkin perlu menabung gaji utuhnya selama 1 hingga 2 tahun—tanpa makan, tanpa bayar listrik, tanpa biaya sekolah anak—hanya untuk membayar biaya terbit satu makalah ilmiah.
2. Aliran Devisa yang Menguap Ke mana uang puluhan juta itu pergi? Ia tidak berputar di dalam negeri untuk membangun laboratorium kampus atau menambah koleksi perpustakaan nasional. Uang itu mengalir deras ke rekening perusahaan multinasional di Amsterdam, London, atau New York yang margin keuntungannya sudah mencapai 40%.
Kita sedang menyaksikan capital flight (pelarian modal) terselubung. Dana hibah riset yang berasal dari pajak rakyat Indonesia, alih-alih digunakan untuk pengembangan iptek lokal, justru habis tersedot hanya untuk “menyewa lapak” publikasi di luar negeri. Dosen kita berdarah-darah secara finansial demi memenuhi beban administrasi (BKD) dan syarat kenaikan pangkat, sementara korporasi global memanen profit dari keringat mereka.
Paradoks Riset Indonesia: “Raja” Open Access yang Terjebak
Di tengah kemuraman narasi finansial tersebut, terdapat satu fakta mengejutkan yang jarang diketahui publik—sebuah anomali yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional namun justru sering diabaikan.
Dalam peta global literasi terbuka, Indonesia bukanlah pemain pinggiran. Faktanya, Indonesia adalah kontributor jurnal Open Access terbesar di dunia dalam direktori DOAJ (Directory of Open Access Journals). Dengan lebih dari 2.400 jurnal terdaftar, kita mengalahkan negara-negara adidaya sains seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Kehebatan Indonesia tidak berhenti di situ. Mayoritas jurnal ini menggunakan model Diamond Open Access. Ini adalah bentuk paling murni dari demokratisasi pengetahuan: gratis untuk dibaca oleh publik, dan gratis untuk ditulis oleh peneliti. Biaya operasionalnya ditanggung secara gotong royong oleh universitas dan asosiasi profesi melalui sistem Open Journal Systems (OJS).
Namun, di sinilah letak ironi yang menyakitkan.
Meskipun memiliki infrastruktur publikasi mandiri yang paling masif dan demokratis di dunia, kebijakan riset nasional kita justru masih mendewakan jurnal komersial Barat. Sistem kenaikan pangkat dan prestisius akademik masih berkiblat pada indeks seperti Scopus dan Web of Science (WoS).
Jurnal-jurnal lokal mandiri (OJS) yang kita bangun dengan susah payah sering kali dianggap sebagai “kelas dua” atau “kelas kampung”. Dosen ditekan, bahkan diwajibkan, untuk mempublikasikan karya di jurnal berbayar mahal yang APC-nya setara dengan 6 hingga 10 bulan gaji mereka.
Kita seperti seorang raja yang memiliki lumbung padi sendiri yang melimpah, namun memaksa rakyatnya untuk membeli beras impor dengan harga selangit demi gengsi. Kita memiliki “emas” berupa kedaulatan data dan infrastruktur publikasi, namun kita menukarnya dengan “loyang” pengakuan semu dari oligopoli penerbit asing.
Eksploitasi Tenaga Kerja Intelektual: Valuasi Ekonomi dari “Kerja Bakti” Global
Aspek paling gelap dan sering diabaikan dari industri ini adalah ketergantungannya yang mutlak pada apa yang disebut oleh para kritikus sebagai eksploitasi tenaga kerja intelektual (unpaid labor).
Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong. Penelitian terbaru mencoba menghitung “valuasi ekonomi” dari kerja gratis yang dilakukan dosen dan peneliti saat me-review jurnal. Estimasi global menunjukkan bahwa setiap tahunnya, para peneliti menyumbangkan waktu mereka senilai US$ 1,1 miliar hingga US$ 6 miliar hanya untuk melakukan peer review.
Bayangkan sebuah perusahaan konsultan global yang mendapatkan jasa analisis ahli senilai miliaran dolar tanpa mengeluarkan uang sepeser pun untuk gaji karyawan. Itulah model bisnis penerbit jurnal.
Di Indonesia, realitas ini terasa lebih pahit. Dosen kita, yang sudah terhimpit oleh beban administrasi dan pengajaran yang padat, melakukan pekerjaan ini di sela-sela waktu istirahat mereka. Mereka memeriksa naskah rumit di malam hari atau akhir pekan, mengambil waktu dari keluarga, demi menjaga kualitas sains global.
Sementara penerbit memonetisasi hasil kerja keras ini menjadi dividen bagi pemegang saham, para reviewer tidak mendapatkan kompensasi finansial sepeser pun. Ini bukan lagi sekadar “pengabdian masyarakat ilmiah”; ini adalah bentuk eksploitasi kapitalis modern terhadap tenaga kerja akademik yang dinormalisasi secara sistemik.
Ancaman Integritas Baru: Skandal Paper Mills dan Bias AI
Jika ketidakadilan ekonomi belum cukup buruk, industri ini kini sedang menghadapi krisis kepercayaan yang lebih fundamental: runtuhnya integritas. Tekanan sistemik “Publish or Perish” (terbitkan atau binasa) telah melahirkan pasar gelap akademik yang mengerikan.
Kasus paling mencolok adalah skandal Wiley-Hindawi yang baru-baru ini mengguncang dunia akademik. Salah satu penerbit terbesar di dunia ini terpaksa menarik kembali (meretraksi) secara massal antara 8.000 hingga 11.300 artikel yang terbukti palsu atau cacat integritas. Ribuan artikel ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan produk dari “Paper Mills” (pabrik kertas)—sindikat terorganisir yang menjual kepenulisan di jurnal ilmiah menggunakan data palsu.
Dampaknya sangat masif. Wiley melaporkan kerugian finansial hingga $40 juta akibat hilangnya pendapatan dan reputasi. Skandal ini membuktikan bahwa model bisnis APC yang mengejar volume (makin banyak artikel terbit, makin banyak uang masuk) sangat rentan disusupi artikel sampah. Ketika profit menjadi panglima, pintu gerbang kualitas menjadi longgar.
Di sisi lain, respons penerbit terhadap teknologi baru justru melahirkan diskriminasi bentuk baru: Bias AI.
Penerbit kini menggunakan detektor AI untuk menyaring naskah yang masuk. Ironisnya, studi menunjukkan alat-alat ini memiliki bias yang kuat terhadap penulis non-native English speakers, termasuk peneliti Indonesia.
Tulisan asli dari peneliti kita sering kali dideteksi secara keliru (false positive) sebagai buatan AI hanya karena pola bahasanya yang cenderung sederhana, baku, dan kurang kompleks dibandingkan penutur asli (native). Ini menambah lapisan hambatan baru yang kejam: peneliti Indonesia sudah berjuang keras menulis dalam bahasa asing, membayar mahal, dan kini dituduh curang oleh algoritma yang bias.
Dinamika Terbaru: Disrupsi, Regulasi, dan Artifisial
Selain skandal integritas, ekosistem publikasi ilmiah global saat ini sedang mengalami turbulensi hebat yang didorong oleh tiga kekuatan utama: kebijakan radikal Eropa, revolusi AI, dan regulasi pendidikan nasional. Inilah perkembangan terbaru yang perlu Anda pahami:
1. Efek Samping “Plan S” bagi Indonesia Eropa melalui konsorsium “cOAlition S” meluncurkan Plan S, sebuah inisiatif mulia yang mewajibkan semua riset didanai publik harus langsung terbuka (Open Access) tanpa embargo.
Namun, bagi negara seperti Indonesia, inisiatif ini bagaikan pisau bermata dua. Karena Indonesia tertinggal dalam negosiasi paket “Read & Publish” (model di mana institusi membayar borongan untuk baca sekaligus terbit), kita terjebak dalam kerugian ganda (double spending). Institusi kita masih membayar langganan mahal agar bisa membaca, sementara dosen kita secara individu masih harus membayar APC mahal agar bisa terbit. Tanpa kesepakatan nasional seperti yang dilakukan Jerman, devisa kita terus terkuras dari dua arah.
2. AI: Kawan atau Lawan? Kehadiran AI Generatif (seperti ChatGPT) menciptakan kekacauan sekaligus harapan. Di satu sisi, ia memicu banjir artikel palsu dari pabrik jurnal. Namun di sisi positif, AI berpotensi menjadi “Penyetara Bahasa” (Language Equalizer).
Bagi peneliti Indonesia, hambatan terbesar sering kali bukan kualitas riset, melainkan kendala bahasa Inggris. Dengan bantuan AI sebagai asisten penyunting, dosen kita kini bisa menghasilkan narasi bahasa Inggris yang setara dengan penutur asli (native). Ini bisa mendisrupsi hegemoni bahasa yang selama ini menjadi alasan penolakan naskah dari negara berkembang.
3. Angin Segar Regulasi: Permendikbudristek No 53/2023 Mungkin ini adalah kabar paling melegakan di dalam negeri. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 26, pemerintah Indonesia secara berani menghapus kewajiban skripsi/tesis harus diterbitkan di jurnal sebagai syarat kelulusan mutlak (dikembalikan ke otonomi kampus).
Dampaknya sangat masif. Kebijakan ini memutus rantai permintaan (demand) putus asa dari mahasiswa yang selama ini menjadi mangsa empuk jurnal predator. Mahasiswa kini bisa lulus dengan membuat prototipe atau proyek, bukan sekadar menyumbang sampah kertas di jurnal abal-abal. Meskipun dosen masih terikat tuntutan publikasi untuk kenaikan pangkat, setidaknya beban di pundak mahasiswa telah diangkat, menggeser fokus dari kuantitas semu menuju kualitas nyata.
Refleksi: Mengembalikan Sains kepada Manusia
Apa yang bisa kita pelajari dari bentangan sejarah industri ini? Bahwa sistem yang ada saat ini bukanlah hukum alam yang tak bisa diubah. Itu adalah konstruksi manusia, dan manusia juga yang bisa meruntuhkannya.
Kita sedang bergerak menuju dua dunia yang terpisah. Satu dunia adalah klub eksklusif berbayar mahal yang dikuasai oligopoli penerbit. Dunia lainnya adalah komunitas terbuka, kolaboratif, dan inklusif yang sedang kita bangun di rumah sendiri.
Bagi Anda, para pembaca, akademisi, atau pemerhati ilmu pengetahuan, sadarilah kekuatan posisi Anda. Jangan lagi silau semata pada label “Internasional”. Mari mulai menghargai platform pengetahuan yang terbuka dan adil.
Pada akhirnya, nilai sejati dari ilmu pengetahuan tidak terletak pada seberapa mahal biaya untuk menerbitkannya, atau seberapa tinggi margin keuntungan penerbitnya. Nilai sejati sains ada pada seberapa besar ia mampu membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan penderitaan. Dan misi suci itu tidak seharusnya memiliki price tag yang mencekik.
Mari kita rebut kembali kedaulatan pengetahuan kita.